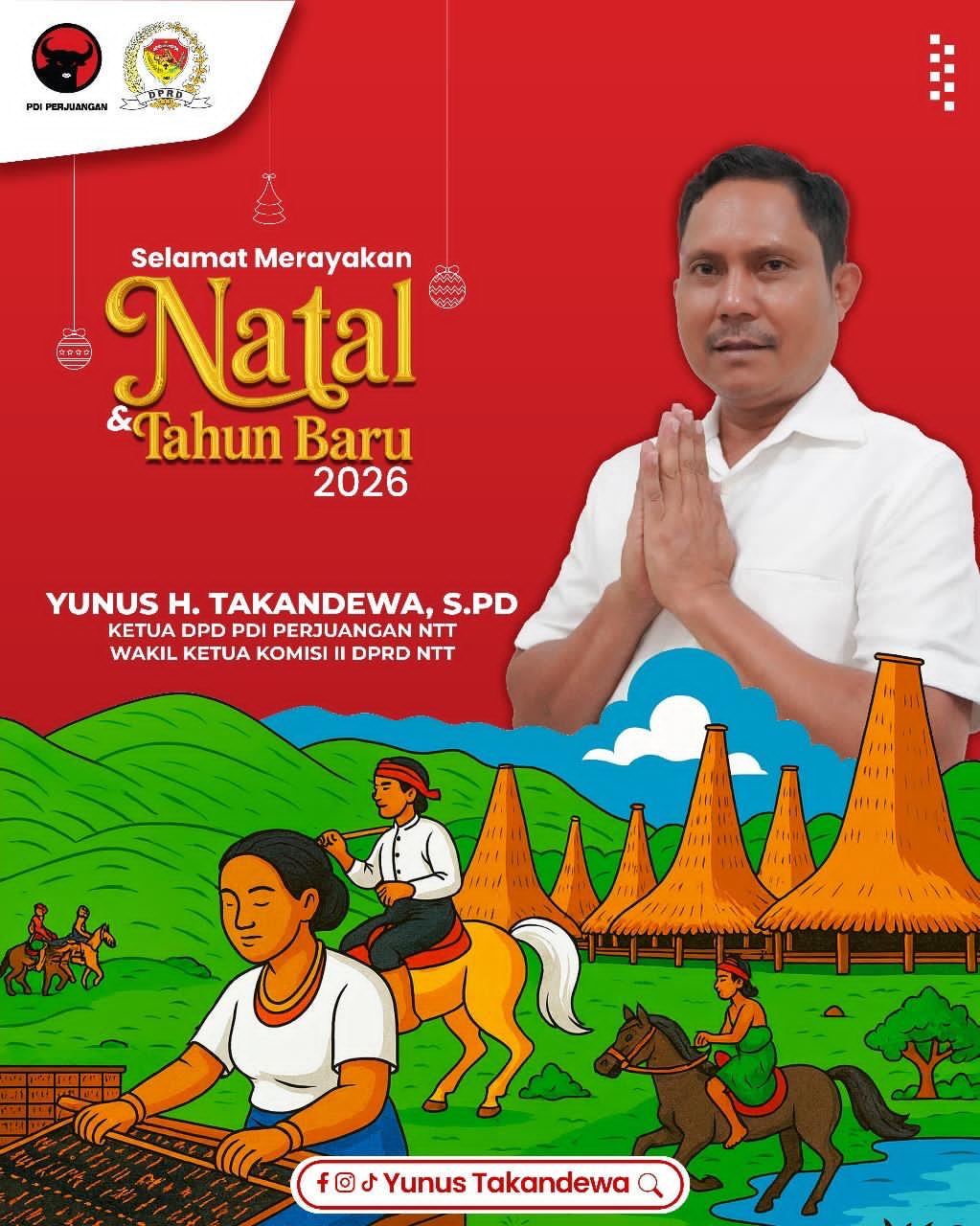Oleh: Yustinus Ghanggo Ate
Asisten Riset pada Endangered Language Catalogue (ELCat) Regional Indonesia, National Science Foundation, 2013-sekarang dan Staf Pengajar pada STKIP Weetebula, Sumba, NTT.
Tahun lalu, di banyak media nasional dan maupun lokal seperti Kompas (25/3/2015; 10/12/2015), Victory News (10/6/2015), hangat diberitakan terkait bahasa-bahasa lokal yang terancam punah dan RUU Bahasa Daerah yang diinisiasi DPD RI. Kesadaran media mengangkat isu ini dan langkah keberpihakan DPD RI sangat tidak biasa, menyegarkan, strategis dan solutif di tengah kegentingan bahasa lokal. Berbanding terbalik dengan yang terjadi di 2014 ketika kurikulum 2013 yang digulirkan menihilkan signifikansi pengajaran bahasa daerah di sekolah. Tulisan ini mencoba mengetengahkan mengapa bahasa daerah sangat penting dan strategis dari perspektif yang berbeda yakni dalam bingkai pembangunan human capital (modal manusia) dan social capital (modal sosial).
Area praksis bahasa, khususnya bahasa daerah, selama ini seolah melulu bereksistensi di rana fungsi bahasa daerah itu sendiri, sekadar perkakas komunikasi bagi komunitas tuturnya. Menurut Sapir-Whorf Hypothesis, yang ditelurkan oleh ahli bahasa Edward Sapir dan muridnya Benjamin Whorf, bahasa tidaklah semata-mata sebagai alat ungkap diri, perasaan dan gagasan. Lebih jauh bahasa secara kuat mempengaruhi proses pembentukan pola pikir dan perilaku penuturnya. Bahasa menggambarkan bagaimana penuturnya melihat dunia dari sudut pandang unik. Dan, pikiran yang khas dari penuturnya adalah sama sekali tidak dapat dipahami oleh penutur bahasa di luar komunitas tuturnya. Searah dengan tesis Alessandro Duranti, antropolinguist dari Universitas California, yakni “bahasa juga membentuk dunianya, menciptakan dunianya.” Ini menunjukkan bahwa secara kuat bahasa mampu membangun peradaban dan sekaligus mentranformasi peradaban manusia penggunanya.
Pembangunan Berbasis Bahasa Lokal
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Konsep pembangunan berbasis bahasa lokal adalah konsep yang sama sekali tidak baru dan pendekatan pembangunan ini diaplikasikan oleh SIL International dan UNESCO di negara-negara dunia ketiga.
Menurut UNESCO (2012) pendekatan ini adalah aksi pembangunan terencana yang mem-vital-kan bahasa daerah dalam proses menuju perubahan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan kebutuhan spritual. Konkritnya adalah pendekatan pembangunan model ini dimulai dari pemberantasan iliterasi dengan menggunakan bahan ajar informatif berbahasa daerah yang meliputi banyak isu seperti pertanian dan sanitasi terlebih isu-isu yang menjadi fokus Millenium Development Goals (MDGs) dan Education for All (EFA). Pendekatan ini percaya bahwa perubahan harus dimulai dari mindset.
Di banyak wilayah lain di dunia seperti di Benin, Chad, Thailand, dan Burma, bahasa daerah dipandang sebagai bagian vital dari grand design pembangunan. Contoh kasus di Benin, Afrika, tepatnya di Komunitas bahasa Waama, pendekatan pembangunan ini dilakukan oleh SIL International dengan salah satu fokus isu utama mengurangi tingkat kematian bayi. Komunitas Waama adalah komunitas dengan angka kematian bayi yang tinggi. Kasus ini sama dengan di NTT, yang angka kematian bayinya termasuk tertinggi di Indonesia, angka kematian bayi tahun 2012 tercatat 14/100.000 kelahiran hidup atau 1.350 bayi meninggal saat persalinan (media daring republika, 17/5/2013). Di sana proyek penurunan angka kematian bayi dimulai dari belajar membaca dalam bahasa daerah untuk para Ibu di kelas literasi. Di kelas ini para Ibu dapat mengakses informasi dasar kesehatan dalam bahasa mereka. Para Ibu belajar betapa pentingnya check up rutin pada masa prenatal dan menjalani proses pengobatan terhadap berbagai penyakit yang diidap hingga persalinan di pusat kesehatan masyarakat. Hasilnya angka kematian bayi terbukti menurun, banyak nyawa terselamatkan. Fakta ini secara jelas mematahkan keraguan akan kapabalitas komunitas etnolinguistik yang selama ini dianggap sama sekali tidak memiliki modal kuat untuk berubah.
Di sisi lain, implementasi konsep ini berkontribusi baik bagi upaya pemertahanan bahasa daerah di tengah gempuran bahasa-bahasa dominan seperti Bahasa Indonesia, dan Inggris serta Melayu dan aneka dialeknya, salah satunya Melayu Kupang. Seperti yang terjadi selama ini di Indonesia penguatan bahasa nasional memakan korban bahasa daerah yang tidak sedikit. Berdasarkan data Lewis et.al. (2015) dari total 719 bahasa di Indonesia, 13 bahasa punah, 75 hampir punah, dan 266 terancam punah. Bahkan menurut kompas.com (15/6/2015), jumlah bahasa punah adalah 14. Sukar dibayangkan ketika bahasa-bahasa daerah dan warisan-warisan peradaban di dalam bahasa-bahasa tersebut, pembentuk identitas kebhinekaan kita, punah. Oleh Alan Dench and Slamet Setiawan (2011) peristiwa ini disebut sebagai the most catastrophic loss of heritage in human history atau ‘tsunami bagi warisan sejarah manusia’.
Pelibatan Bahasa Daerah di NTT: Contoh Kasus
Menengok konsep dan aksi pembangunan daerah kita di NTT dan Indonesia adalah melihat kecenderungan menempatkan posisi bahasa daerah ke pinggiran realitas pembangunan. Di mana peran bahasa daerah sebagai wadah diambil alih oleh bahasa dominan yang cara pandang dunianya kontras dengan penutur bahasa daerah, yang karekteristik penuturnya bertolakbelakang dengan penutur bahasa daerah. Alasan yang paling mungkin mengapa ini terjadi adalah dikarenakan orientasi pembangunan kita masih bersifat programatik, tanpa ideologi pembangunan yang rigid, dan bukan sebaliknya mengarusutamakan pembangunan paradigmatik. Sehingga yang menyusun perencanaan pembangunan, antara lain pemerintah dan NGO, sangat jarang dan mungkin sama sekali tidak pernah melihat dan menimbang isu bahasa daerah sebagai unsur paling mendasar suksesnya sebuah proyek pembangunan. Penegasian unsur lokalitas yang otentik ini berdampak besar pada sukar beranjaknya paradigma masyarakat lokal terhadap pentingnya menyesuaikan diri dengan dunia yang terus bergerak ke depan tanpa menanggalkan isi budaya luhurnya.
Pelibatan bahasa daerah dalam pembangunan sosio-ekonomik kita di NTT adalah sine quo non ‘keharusan.’ Prinsip ini didasari oleh beberapa kenyataan mendasar, pertama, heterogenitas etnolinguistik NTT. Adalah kelainan jika berbicara Pembangunan NTT tanpa memandang keberadaan NTT sebagai wilayah etnolinguistik yang beragam dan kaya. Dalam buku ‘A guide to the people and Languages of Nusa Tenggara’ oleh Grimes dan kawan-kawan (1997) dikatakan bahwa Nusa Tenggara lebih khususnya NTT adalah ‘melting pot’, tempat bertemunya dua rumpun bahasa besar di dunia yakni Rumpun Bahasa-bahasa Austronesia dan Non-Austronesia yang berjumlah 60 ethnolinguistik.
Kedua, sifat dari kantong-kontong kemiskinan dan ketertinggalan di NTT adalah angka buta huruf tinggi, bahasa daerah sebagai bahasa pertama, kemampuan berbahasa Indonesia lemah, masalah gender, dan angka partisipasi sekolah di bawah rata-rata. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT (2013) angkah buta huruf di NTT adalah 800 ribu orang dari total penduduk NTT 5.3 juta jiwa. Angka ini signifikan apalagi jika ditambah dengan yang belum terdata. Disamping itu, menurut laporan hasil Riset Kesehatan Daerah (Riskesdas) NTT (2013) kantong-kantong ini identik dengan angka kematian ibu dan bayi tinggi, malaria, dan rawan diare, bahkan ini penyebab kematian tertinggi di NTT pada bayi 1-11 bulan (31,45%) dan balita 1-4 tahun (25,2%).
Tantangan dan Harapan
Pada tahun 2028-2030 Indonesia diperhitungkan akan berada pada titik kulminasi bonus demografi. Ini adalah peluang emas jika angka manusia non produktif kita defisit dan sekaligus petaka jika angka manusia non produktif kita tidak terkendali. SDM kita mesti bermutu tinggi agar kesiapan kita prima dalam menjemput momentum. Untuk mengantisipasi ini maka ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, pertama, perencanaan pembangunan di locus termiskin dan tertinggal mesti menempatkan bahasa daerah pada posisi sentral yang akan sangat membantu cepat, tepat, dan efektifnya pembangunan.
Kedua, keterlibatan para peneliti bahasa dalam mendokumentasikan bahasa daerah, memetakan kompleksitas karekteristik penutur, dan mendesain modul-modul literasi dan numerasi dalam bahasa daerah dan booklet-booklet informatif sosio-ekonomi berbahasa daerah, sangatlah penting.
Ketiga, meminjam pikiran Eep Saifulloh Fatah yakni perlu adanya politik bahasa, tetapi di sini adalah politik bahasa yang tidak sekadar superfisial dan tidak timpang. Sejak Indonesia merdeka, politik bahasa di Indonesia lebih menitikberatkan pada bahasa Indonesia sebagai alat perantara antarmasyarakat berbeda bahasa.
Bermula ketika naskah asli Sumpah Pemuda diubah oleh Soekarno dan Muhammad Yamin di 1950an dari seharusnya “menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia” menjadi
“berbahasa satu, bahasa Indonesia.” Ini terjadi akibat kepentingan politik post-kolonial. Politik bahasa di era kekinian perlu ditransformasi yang mana bahasa lokal atau bahasa daerah perlu diberi peran kuat dan strategis: memperkuat pembangunan manusia dan sosial penuturnya. Berharap sikap politik bahasa daerah yang diambil DPD RI tidak men-subordinat-kan keberadaan bahasa lokal dengan fungsi yang kurang strategis dan tidak memberi efek domino.
Akhirnya, besar harapan para pemangku kepentingan di daerah, seperti pemerintah dan lembaga keagamaan, lebih memberi perhatian khusus dan peran lebih substantif kepada bahasa daerah dalam mendesain pembangunan lokal. Dan, semoga tulisan ini menjadi sumbangan pemikiran yang konstruktif dan positif bagi kita semua untuk terlibat mengawal, memelihara, mempertahankan warisan leluhur kita.